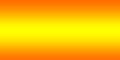Apa kabar? Semoga baik-baik dan sehat selalu. Salam kenal. Banyak terima kasih atas emailnya. Saya mohon maaf bahwa kamu mencari-cari saya, tapi tidak pernah ketemu. Saya memang pos utama-nya di Pasca dan IRB, tapi masih tetap mengajar di S-1 Sejarah. Biasanya kalau di Pasca, kalau saya tak ada di tempat bisa tanya ke Sekretariat dan mereka tahu di mana saya berada. Bisa juga saya ditemui di PUSdEP, di lantai dua Realino Utara, dekat Beringin Sukarno.
Saya sudah lihat blog-mu dan ternyata menarik. Paparan maupun foto-foto di sana tampak mengesankan. Petualang juga kau ternyata. Hebat! Oya, terima kasih sudah mau baca "Chicago, Chicago." Semoga dapat menjadi inspirasi ala kadarnya. Belum punya bukunya ya? Saya tidak tahu apakah saya masih punya, tapi kalau ada waktu silakan mampir ke kantor PUSdEP. Nanti kalau ada saya beri satu, entah untuk sendiri atau untuk temanmu.
Semoga kamu tetapi rajin berusaha dan berjuang, dan semoga tak lama lagi segera mendapatkan tempat yang sesuai.
Sekian, sampai ketemu suatu saat nanti. GBU
Penulis:Baskara T. Wardaya
Tebal: 278 hlm.
Setiap kali me

nyaksikan seseorang dengan gigih menyuarakan kebajikan, setiap kali pula kehidupan ini niscaya masih punya masa depan. Kalimat itulah yang barangkali pantas untuk menggambarkan pesan yang hendak disampaikan dalam buku ini.
Ibarat kristal, kehidupan memancarkan banyak warna: ada cinta, ketulusan, ketabahan, kesederhanaan, juga sebaliknya: ada kebencian, amarah, juga ketamakan. Adalah Romo Baskara, anak manusia yang tetap gigih meniti hidupnya dalam jalan pelayanan dan cinta. Melalui buku yang ditulisnya ini, ia memendarkan suara lain, suara yang bersumber dari hati nurani, suara yang dipenuhi dengan cinta kasih, yang hendak mengingatkan kita semua bahwa kehidupan masih memiliki masa depan, kehidupan itu harus tetap diafirmasi.
Di tengah pragmatisme dunia yang semakin kuat, di mana sangat sedikit pribadi yang bersedia berbagi dalam keikhlasan, kehadiran buku ini ibarat sebuah oase yang menyejukkan kehidupan. Pengalaman menimba ilmu di negeri Paman Sam selama kurang lebih sepuluh tahun, serta perjumpaan dengan pribadi-pribadi yang mengesankan, menjadi bahan renungan yang sangat berharga bagi penulis sehingga reportase kemanusiaan dalam buku ini sanggup mengantarkan pembacanya menelisik palung-palung kehidupan.
Ternyata, bukan hanya dari narasi-narasi besar manusia dapat belajar tentang makna dan nilai-nilai kemanusiaan, tapi juga dari serpihan kejadian sehari-hari—keagungan nilai-nilai kemanusiaan itu menyibakkan dirinya. Nilai-nilai kemanusiaan yang tertorehkan dalam buku ini muncul dari beragam rupa momen kehidupan yang terlihat begitu lumrah.
Sungguh mengesankan, ketika sang Romo menggambarkan kekagumannya pada keindahan dan kecantikan teman perempuan bulenya di akhir tulisan “Di Tepian danau Michigan”. “Misty, tentunya kau masih ingat, sore itu kita mau mengunjungi gereja tua di atas bukit sana. Di tengah jalan, saat kita berhenti untuk membeli bahan bakar, tiba-tiba salju turun. Kau keluar sejenak dari mobil dan dengan kedua tangan tengadah menyambut sang salju. Seserpih salju menempel di rambutmu yang panjang. Indah sekali. Kau pun tersenyum manja. Sore yang sangat mengesankan.” Membaca tulisan itu, saya kemudian teringat dengan religiositas Romo Mangun yang kerap diwarnai oleh decak-kagum pada kecantikan dan keindahan perempuan. Para seniman di zaman renaisans sering menempatkan keelokan rupa tubuh perempuan sebagai medium bagi upaya memburu keindahan dan keagungan yang bersumber dari kesucian sang Ilahi.
Kemanusiaan sang Romo tidak hanya tampak dalam mengagumi keindahan, atau khususnya kecantikan perempuan. Di tengah-tengah kesibukan penelitiannya, sang Romo tidak luput dari kancah pergumulan hak-hak asasi manusia (HAM) sedunia, yang seringkali mengambil AS sebagai gelanggang. Di sana ia berjumpa dengan Li Lu, seorang veteran gerakan mahasiswa Cina yang luput dari pembantaian massal di Lapangan Tienanmen, tanggal 4 Juni 1989. Sebagai anggota delegasi Indonesia, sang Romo pertama kali berkenalan dengan Li Lu dalam konferensi PBB tentang HAM di musim panas 1992 di Wina, Austria. Sesudah itu, keduanya berpisah lama dan tidak berkomunikasi. Tiba-tiba, ia membaca tulisan di majalah The New Yorker, bahwa di bulan Mei 1996, Li Lu, si pejuang demokrasi dari Cina itu, telah lulus dari Columbia University dengan tiga gelar sekaligus: sarjana muda di bidang ekonomi, sebuah gelar di bidang hukum, dan MBA. Suatu prestasi yang luar biasa.
Berangkat dari kisah Li Lu di atas, reportase kemanusiaan sang Romo tergores apik dalam tulisan “Kisah Pilu Kawan Li Lu”. Dengan semangat yang pantang menyerah dan berbalut visi kemanusiaan, hambatan sekokoh batu karang pun akan mampu dirobohkan. Dengan tekad kuat untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih demokratis di negerinya, Li Lu akhirnya berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan hidup dalam pengasingan, bahkan ia menorehkan prestasi yang tidak biasa. Kisah tentang Li Lu ini telah memberikan inspirasi bagi sang Romo dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaannya.
Sebuah perjumpaan yang tak kalah mengesankan adalah ketika sang Romo untuk kali pertama bertemu dengan sastrawan kondang Pramoedya Ananta Toer di New York dalam sebuah sesi wawancara yang kemudian dikemas dalam tulisan “Pram, Ayam, dan Segenggam Dendam. Pengakuan Pram tentang kehidupannya semasa ditahan di pulau Buru benar-benar telah membenamkan sang Romo pada penghayatan betapa pentingnya semangat untuk betahan hidup dan kemampuan berdamai dengan sejarah pahit penindasan.
Bayangkan, hanya dengan bantuan telur-telur dari ayam peliharaannya, Pram mampu melahirkan Tetralogi Pulau Buru yang masyhur itu. Juga perlakuan keji dari pemerintah orde baru ternyata tidak membuat Pram larut dalam balutan dendam. Bahkan dari hal itu, Pram telah meninggalkan pelajaran berharga bagi generasi sesudahnya bahwa untuk tetap lestarinya nilai-nilai kemanusiaan, dendam pribadi terhadap sejarah harus ditanggalkan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki visi peradaban, yang mampu melihat horizon kehidupan dalam cakrawala pandang kemanusiaan, bukan berdasar pada egoisme yang mengerdilkan.
Banyaknya pengalaman penulis yang mengesankan dengan orang-orang AS yang secara umum dikategorikan sebagai “orang Barat”, membuat ia mempertanyakan kembali dikotomi “orang Barat versus orang Timur” yang sering ia baca dalam buku-buku pengantar antropologi. Dalam tulisan “Adat Barat Kultur Timur”, penulis menegaskan penilaiannya bahwa tak selamanya orang Barat itu lebih individualis, kasar, egoistis, bila dibandingkan dengan orang Timur. Dalam taraf tertentu, orang Timur yang konon terkenal ramah justru sering menunjukkan agresivitas yang lebih tinggi. Contoh terdekat adalah kondisi masyarakat Indonesia akhir-akhir ini yang sangat mudah disulut amarahnya, sehingga konflik-konflik sosial mudah terjadi.
Memang strereotip tentang orang Timur yang halus, yang ramah tamah, dan suka menolong sesamanya, yang selalu dikontraskan dengan stereotip tentang orang Barat yang kasar, yang individualistis, dan yang tidak suka menolong sesamanya, sudah saatnya dibuang jauh-jauh dari skema kognitif kita.
Seperti umumnya buku reportase perjalanan, buku ini juga menghadirkan cerita-cerita unik yang hanya terjadi dalam momen-momen tertentu. Barangkali yang membedakan dengan buku lainnya adalah adanya niat kuat dari penulisnya untuk menghadirkan sesuatu, tidak hanya mendiskripsikan fakta secara linear. Sang Romo dengan penuh ikhtiar berusahan memoles setiap kejadian yang dijumpainya dengan spirit religiositas dan visi humanisme, sehingga kejadian-kejadian sederhana sehari-hari hadir dalam nuansa keagungan dan keutamaan. Bagi sebagian pembaca, pembacaan sang Romo mungkin terkesan berlebihan, terlalu berbaik sangka, tidak kritis, sehingga kebusukan hidup sehari-hari luput dari pengamatan.
Ada catatan yang perlu diberikan terhadap kumpulan reportase penulis buku ini. Sebagai rohaniawan, kemungkinan besar ia bergerak dari lingkungan satu ke lingkungan lain, di mana semua kebutuhan hidupnya yang dasar mulai dari sandang, pangan, papan, sudah dipenuhi oleh orang lain, khususnya kongregasinya. Sebab tidak selamanya, Paman Sam begitu ramah kepada orang-orang dari Dunia Ketiga yang ingin menuntut ilmu di sana.
Kesaksian betapa Paman Sam tak selamanya menyuguhkan keramahan disampaikan oleh George Junus Adijtondro dalam kata pengantar buku ini. Pada waktu ia menerima beasiswa Hubert H. Humphrey dari Pemerintah AS tahun 1981/2 ia menemukan kecurangan-kecurangan yang justru dilakukan oleh para dosennya di Universitas Cornell. Para penerima beasiswa diwajibkan menempati sebuah apartemen miskin fasilitas tapi dengan harga selangit yang dikelola oleh para dosen dengan maksud hendak mendaur ulang uang beasiswa yang telah diberikan. Barangkali motif dari praktik-praktik kecurangan itu bersumber dari kekerdilan berpikir bahwa uang beasiswa itu toh pada dasarnya bersumber dari pajak rakyat Amerika sendiri.
Apapun yang disampaikan Romo Baskoro dan George J. Aditjondro hanyalah serpihan kisah dari kompleksnya dinamika kehidupan masyarakat AS. AS adalah negara besar yang memanggul sekian banyak atribut--negara dengan kemajuan teknologi yang tiada duanya, simpul dari sekian banyak praktik kebudayaan, laboratorium nyata bagi praktik demokrasi, dan medan subur bagi praktik-praktik budaya massa. Maka dari itu, kesan yang diperoleh atas kehidupan di AS sangat tergantung dari siapa yang menilainya.
Pertanyaan mengapa buku ini hanya menyuguhkan cerita-cerita manis seputar kehidupan masyarakat AS tentunya tidak bisa dilepaskan dari siapa penulisnya. Pertama, penulisnya adalah seorang rohaniawan yang memang ditugaskan tidak sekedar untuk belajar, melainkan juga melayani masyarakat. Memanggul tugas pelayan inilah yang mengkondisikan penulis buku ini untuk selalu berpikir positif atas segala sesuatu, juga terhadap hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Kedua, hampir sebagian besar waktu penulis dihabiskan di Milwaukee dan kota-kota kecil di negara bagian Wisconsin di mana masyarakatnya masih cukup kuat memegang tradisi dan nilai-nilai keagamaan. Barangkali, kejadiannya akan berbeda bila penulis tinggal di New York atau Los Angeles, yang saban waktu dipenuhi dengan kemaksiatan (baca: hiburan) dan angka kriminalitas yang tinggi.
Lantas mengapa Chicago yang kemudian dipilih menjadi ikon buku ini, seakan-akan cerita yang dibangun berlatar belakang di kota raya itu. Alasannya sederhana, di samping lebih dikenal orang awam, Chicago adalah kota besar terdekat dari Wilwaukee (tempat penulis menimba ilmu di Universitas Marquette) yang sering dikunjungi oleh penulis untuk keperluan riset studinya.
Terlepas dari semua itu, buku ini pantas diapresiasi--buku yang tak hanya sekedar catatan personal, melainkan juga sebagai rekaman sejarah pergulatan hidup, di mana manusia ingin membangun peradaban yang semakin manusiawi.
dari :http://www.ruangbaca.com
 Badan Tenaga Nuklir (Batan) menyarankan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalbar, karena memiliki deposit tambang uranium. Hal ini terungkap dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2008. Namun Kalbar harus menggaet negara maju dan memerhatikan faktor keamana n dan limbahnya. “Setuju jika Kalbar ingin memanfaatkan uranium yang ada di Melawi, tetapi harus pandai-pandai menggunakan teknologi agar kita tidak difitnah oleh negara-negara maju. Saya pikir kita harus menggaet salah satu di antara negara maju itu,” kata Dr. Thamrin Usman DEA, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Tanjungpura di Rektorat Untan Sabtu (23/2) kemarin. Dikatakan Thamrin, hal ini merupakan permasalahan mineral strategis di tingkat nasional dan internasional. Rencana pembangunan PLTN tersebut jangan sampai suatu hari nanti malah menyudutkan Indonesia karena memproduksi bom massal dari nuklir. Indonesia juga nanti yang terkena getahnya seperti yang dilakukan oleh Amerika kepada Irak dan Iran. “Secara teknologi saya pikir kita bisa merapat ke Amerika atau ke Jepang agar ada bumper (tameng, red). Suatu saat nanti kalau kita dikecam karena Indonesia menghasilkan bom masal, maka ada tameng,” kata Thamrin seraya menyebut Perancis untuk dihaet karena negara tersebut salah satu negara yang mengekspor listrik hasil produksi dari bahan bakar nuklir. Dari segi limbahnya, kata Thamrin, PLTN ini tidak ada masalah karena limbahnya bisa diamankan dengan mencampurkan beton, sehingga dapat ditanamkan dalam perut bumi.
Badan Tenaga Nuklir (Batan) menyarankan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalbar, karena memiliki deposit tambang uranium. Hal ini terungkap dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2008. Namun Kalbar harus menggaet negara maju dan memerhatikan faktor keamana n dan limbahnya. “Setuju jika Kalbar ingin memanfaatkan uranium yang ada di Melawi, tetapi harus pandai-pandai menggunakan teknologi agar kita tidak difitnah oleh negara-negara maju. Saya pikir kita harus menggaet salah satu di antara negara maju itu,” kata Dr. Thamrin Usman DEA, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Tanjungpura di Rektorat Untan Sabtu (23/2) kemarin. Dikatakan Thamrin, hal ini merupakan permasalahan mineral strategis di tingkat nasional dan internasional. Rencana pembangunan PLTN tersebut jangan sampai suatu hari nanti malah menyudutkan Indonesia karena memproduksi bom massal dari nuklir. Indonesia juga nanti yang terkena getahnya seperti yang dilakukan oleh Amerika kepada Irak dan Iran. “Secara teknologi saya pikir kita bisa merapat ke Amerika atau ke Jepang agar ada bumper (tameng, red). Suatu saat nanti kalau kita dikecam karena Indonesia menghasilkan bom masal, maka ada tameng,” kata Thamrin seraya menyebut Perancis untuk dihaet karena negara tersebut salah satu negara yang mengekspor listrik hasil produksi dari bahan bakar nuklir. Dari segi limbahnya, kata Thamrin, PLTN ini tidak ada masalah karena limbahnya bisa diamankan dengan mencampurkan beton, sehingga dapat ditanamkan dalam perut bumi.